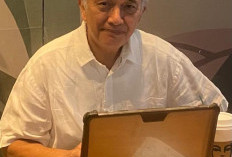Refleksi HPN 2026, 10 Tantangan Jurnalis Indonesia di Era Media Baru

Dr Bagus Sudarmanto, S.Sos, M.Si.-Weradio.co.id-DOK Pribadi
Pew Research Center (2020) juga menemukan mayoritas pengguna media sosial sering menemui berita yang tidak akurat atau menyesatkan, dan kesulitan membedakan antara laporan jurnalistik, opini, dan konten partisan.
Di Indonesia sendiri, tingginya penetrasi media sosial dan pola konsumsi berita yang serba cepat membuat perhatian publik semakin terfragmentasi dan dangkal, sehingga proses verifikasi, konteks, dan keberimbangan kerap terpinggirkan.
Kondisi ini menegaskan tantangan media sosial, disinformasi, dan budaya instan tidak boleh menggeser prinsip dasar jurnalistik seperti independensi, keberimbangan, dan verifikasi sebagai fondasi demokrasi.
Sulitnya, bagaimana pers dapat tetap menjalankan fungsi demokratisnya ketika perhatian publik semakin terfragmentasi, algoritma platform mendominasi distribusi informasi, dan kedalaman wacana publik terus tergerus?
Keenam, disinformasi sebagai ancaman kesehatan ekosistem pers. Banjir hoaks dan disinformasi di ruang digital menggerus kredibilitas pers dan memperlemah posisi jurnalisme profesional sebagai rujukan utama publik.
Ketika informasi palsu menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan berita terverifikasi, pers dipaksa bekerja ekstra untuk mempertahankan kepercayaan publik di tengah arus informasi yang tidak simetris.
Kondisi ini mengindikasikan, tantangan disinformasi tidak semata persoalan teknis verifikasi, tetapi juga menuntut rekonseptualisasi praktik dan peran jurnalisme agar tetap relevan di tengah geliat teknologi digital.
Jurnalisme tidak lagi cukup berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan perlu menegaskan kembali perannya sebagai kurator pengetahuan publik, penafsir konteks, dan penjaga kualitas wacana di ruang digital.
Pers yang sehat mensyaratkan ruang informasi yang bersih, di mana kerja verifikasi jurnalis tetap menjadi rujukan utama publik, sekaligus didukung oleh adaptasi metodologis dan etis terhadap dinamika teknologi.
Lalu, strategi kolaboratif apa yang dapat dibangun antara pers, platform digital, dan publik untuk memutus rantai disinformasi secara berkelanjutan tanpa mengorbankan prinsip dasar jurnalistik?
Ketujuh, tekanan algoritma terhadap independensi redaksi. Ketergantungan media pada platform digital menjadikan algoritma sebagai penentu utama distribusi berita. Judul sensasional dan konten emosional sering kali lebih diuntungkan, sementara liputan mendalam dan isu kepentingan publik cenderung tersisih. Perubahan algoritma Facebook sejak 2018, misalnya, membuat banyak media di Amerika Serikat dan Eropa kehilangan jangkauan pembaca secara signifikan, sehingga mendorong redaksi memprioritaskan konten yang “ramah algoritma” demi mempertahankan trafik.
Kondisi ini memicu kritik bahwa agenda redaksi secara tidak langsung dikendalikan oleh logika platform, bukan oleh pertimbangan editorial. Di Indonesia, tekanan serupa terlihat pada kecenderungan media daring mengoptimalkan judul clickbait, konten viral, dan isu-isu emosional agar sesuai dengan mekanisme distribusi platform media sosial dan mesin pencari.
Dalam praktiknya, liputan investigatif, isu kebijakan publik, atau laporan berbasis data sering kalah bersaing dengan konten yang cepat dikonsumsi dan mudah dibagikan. Ketergantungan ekonomi pada trafik digital ini membuat ruang redaksi berada dalam dilema antara menjaga independensi jurnalistik dan memenuhi tuntutan visibilitas algoritmik. Dalam konteks tema HPN, kemandirian ekonomi pers menjadi sulit dicapai jika ruang redaksi sepenuhnya tunduk pada logika platform global yang tidak selalu sejalan dengan kepentingan publik nasional.
Pertanyaannya, bagaimana media dapat merebut kembali kendali editorial melalui diversifikasi model bisnis, penguatan basis pembaca langsung, dan transparansi algoritmik, tanpa sepenuhnya terjebak pada logika platform digital?
Kedelapan, prekarisasi kerja dan kesehatan profesi jurnalis. Kontrak tidak tetap, upah rendah, dan beban kerja tinggi menjadi realitas banyak jurnalis digital. Kondisi ini bukan sekadar isu ketenagakerjaan, melainkan indikator kesehatan pers itu sendiri. Dalam jangka panjang, prekarisasi berpotensi menggerus profesionalisme dan keberlanjutan profesi jurnalis, karena mendorong praktik kerja serba cepat, multitugas berlebihan, serta ketergantungan pada konten instan yang minim pendalaman. Kajian Deuze dan Witschge (2018) menunjukkan bahwa ketidakpastian kerja yang kronis dapat melemahkan identitas profesional jurnalis dan menurunkan kapasitas mereka menjalankan fungsi kritis sebagai penjaga kepentingan publik.